(Terbit di Harian Pikiran Rakyat, Rabu/15 Desember 2021)
Belum kering wacana mengenai Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang di dalamnya terdapat kalimat “tanpa pesetujuan korban” yang dianggap bisa memicu pergaulan bebas bahkan permisifitas seksual, belakangan muncul berita miring tentang seorang pimpinan pondok pesantren yang memerkosa dan menghamili belasan santriwatinya. Miris dan memprihatinkan pastinya. Walaupun, sepertinya informasi tersebut masih memerlukan identifikasi, verifikasi dan investigasi oleh pihak berwenang terkait dengan tindak pemerkosaan yang ramai diviralkan.
Ada beberapa isu yang perlu dicermati dalam kasus ini, pertama perihal korban yang merupakan peserta didik (santriwati), kedua perihal pesantren dan infrastruktur pendidikan keagamaannya..
Psikologis Korban
Memang mengherankan, peristiwa rudapaksa pimpinan pondok terhadap santriwatinya ini berlangsung dalam rentang waktu 2016-2021. Selama lima tahun dan tidak ada riak kegaduhan di tengah keluarga maupun di masyarakat tetangga pondok. Padahal dalam logika kita dalam waktu lima tahun tersebut pastinya masih ada ruang dan peluang dimana para santriwati korban berkomunikasi dan berinteraksi, termasuk pulang kampung, bertermu dengan keluarganya. Tidak adakah diantara mereka yang bercerita kepada orangtua atau sanak saudaranya di awal-awal mereka “diusili” oleh pimpinan lembaga pendidikan tempat mereka mondok? Selain itu mustahil juga mereka diisolasi sedemikian rupa dalam kurun waktu tersebut tanpa pernah ada peluang berinteraksi dengan masyarakat sekitar, atau keluar pondok untuk sekedar rihlah (bepergian) atau belanja atau apapun yang melepaskannya dari “belenggu” internal pondok? Sehingga mereka bisa melaporkan nasib tragisnya kepada masyarakat, aparat atau bahkan bisa kabur meninggalkan pondok tersebut tanpa perlu kembali lagi sama sekali. Mengherankan, karena kabarnya bahkan ada yang melahirkan hingga kedua kalinya.
Bagaimana jika ternyata fenomena tersebut tidak lepas dari adanya aspek psikologis korban yang terpaksa menerima perlakuan tersebut? Tanpa bermaksud tidak berempati atau tidak bersimpati kepada para santriwati korban dan keluarganya, asumsi ini dimunculkan justru untuk menyingkap tabir dan melacak apa akar penyebab utama terjadinya kasus yang miris dan memprihatinkan ini. Adanya pemaksaan berupa obat-obatan, alkohol, narkoba, hypnosis, atau korban memiliki kondisi fisik/psikologis yang rentan, kondisi terguncang adalah situasi dan kondisi yang sulit diterima sebagai prekondisi terjadinya fenomena itu. Adanya ancaman? Mungkin, walaupun mengherankan juga ketika korban memiliki peluang melepaskan diri dan melaporkannya kepada pihak lain, justru tidak terjadi atau tidak dilakukan. Atau korban didera rasa takut berkepanjangan.
Ada asumsi lain yang memungkinkan hal itu terjadi: indoktrinasi. Tentu dalam suatu pranata sosial atau keagamaan ada doktrin atau faham yang diajarkan, namun indoktrinasi yang dimaksud disini boleh jadi kesengajaran menyimpangkan doktrin yang benar atau memang mengembangkan doktrin yang salah: indoktrinasi ketaatan santri kepada pimpinan pondok, indoktrinasi halalnya hubungan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dipraktikkan, indoktrinasi bahwa orangtua tidak wajib/harus menjadi wali nikah disebabkan alasan tertentu (misalnya karena dianggap kafir), dan indoktrinasi untuk berpura-pura dan menutupi/berbohong tentang “aib” tersebut dari keluarga dan khalayak. Bila benar ada faktor indoktrinasi yang dimainkan, maka pelaku telah memanipulasi faham keagamaan dan kelemahan posisi para korban. Walaupun kejahatan itu tidak beragama, patut disayangkan pelaku sedang berada di etalase lembaga pendidikan keagamaan.
Pesantren-phobia?
Ruang media sosial adakalanya diisi dengan perbicangan dan komentar dari kalangan yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti, tidak faham duduk persoalan sebenarnya, tidak punya data, mengedepankan emosi tanpa disertai penalaran, dan yang gatal kalau tidak berkomentar. Pokoknya asal berkomentar sudah merasa berkontribusi terhadap persoalan bangsa dan masyarakat. Namun diantara efeknya antara lain justru yang begini bisa melahirkan generalisasi yang tidak benar, menggeser akal sehat, menafikan obyektifitas dan menjadi pengadilan yang tidak fair. Apalagi jika ada pihak yang sengaja menggorengnya untuk kepentingan tertentu.
Akankah kita membakar lumbung padi disebabkan kita melihat ada seekor tikus masuk ke dalamnya? Tentu tidak. Pastinya masyakarat berharap segala lembaga pendidikan, baik yang formal dan non formal, yang dikelola pemerintah atau masyarakat, baik pendidikan umum atau khas keagamaan, dapat menjaga marwahnya dengan cara berkarya dan berkinerja sesuai dengan visi, misi dan program-program pendidikan yang luhur. Ada tanggung jawab kolektif kelembagaan untuk memelihara dan merawat branding kependidikan ini dengan sebaik-baiknya. Faktor regulasi sudah hadir untuk memayunginya, tinggal implementasinya yang harus dikelola secara lebih berkualitas lagi.
Sekarang ini berkembang banyak pesantren dan lembaga pendidikan formal berasrama yang performanya maju, bermutu dan melahirkan lulusan yang kompeten. Banyak diantaranya yang mengembangkan kurikulum yang holistik-integratif menyentuh berbagai aspek perkembangan peserta didik, bidang akademik, keagamaan, teknologis, entrepreneurship, dan life/soft skills. Fundamental ajaran keagamaan, muatan kurikulum pendidikan pesantren, proses pembelajaran, profil lulusan, kualifikasi tenaga asatidz (guru/pendidik) dan sumber daya insani pendukung, sarana dan prasarana pesantren, model pengelolaan, dan interaksi dengan lingkungan sosial sekitar, adalah sejumlah komponen yang harus dikelola dan dikembangkan oleh pihak penyelenggara pesantren secara berkelanjutan. Juga hal-hal itu pulalah yang menjadi aspek-aspek pertimbangan para orangtua yang akan menitipkan pendidikan anak-anak mereka, agar tidak ada lagi peristiwa miris dan memprihatinkan.***



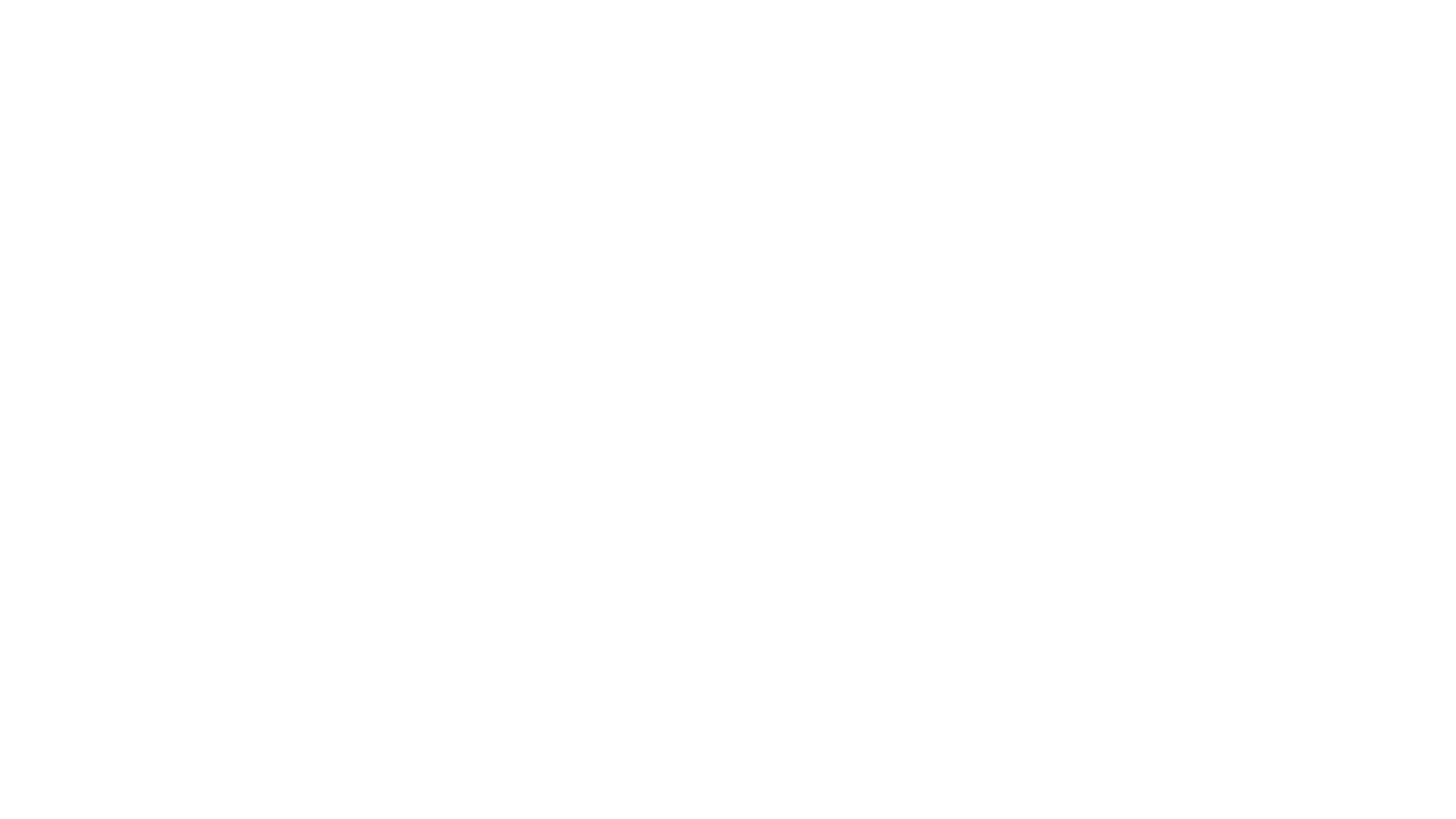
 Radio Unisba - 24STATION
Radio Unisba - 24STATION
